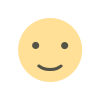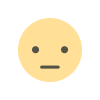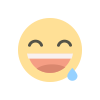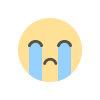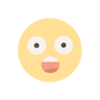Feodalisme dalam Budaya Indonesia: Kemiskinan, Pendidikan, dan Kultus Gelar Habib, Gus, Kyai

Sejarah dan Latar Belakang Feodalisme di Indonesia
Secara historis, masyarakat Indonesia terbentuk oleh warisan sistem feodal sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Struktur sosial kerajaan menempatkan raja dan bangsawan pada puncak hierarki, sementara rakyat biasa berkedudukan sebagai bawahan. Pola relasi patron-klien (tuan dan abdi) yang kuat di era kerajaan terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka Meskipun feodalisme formal (seperti di Eropa abad pertengahan) sudah lama ditinggalkan, sisa-sisanya masih mengakar kuat dalam tatanan sosial-politik modern Dalam praktiknya, hubungan antara pemimpin dan rakyat sering bersifat patronase: rakyat bergantung pada pemimpin untuk bantuan atau perlindungan, dan sebagai imbalannya pemimpin memperoleh loyalitas serta dukungan massa
Pada masa kolonial, Belanda turut memanfaatkan struktur hierarkis tradisional. Para bupati atau priyayi (elit lokal) dijadikan perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, memperkuat budaya feodal di kalangan pribumi. Selepas kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun sistem politik yang egaliter dan demokratis, namun pola pikir feodal sulit hilang seketika. Budaya paternalistik – menghormati pemimpin secara berlebihan bak “raja kecil” – masih kerap dijumpai. Misalnya, dalam politik lokal hingga nasional, muncul dinasti politik dan figur “Bapak” bangsa yang diperlakukan istimewa. Hal ini merupakan cerminan bahwa mentalitas feodal (feudal mentality) warisan masa lalu belum sepenuhnya luntur. Akibatnya, proses pembangunan dan modernisasi acap tersendat, karena pengambilan keputusan maupun distribusi sumber daya masih dipengaruhi oleh hierarki sosial non-formal tersebut
Pengaruh feodalisme juga tampak dalam ketimpangan sosial-ekonomi yang menonjol. Sejumlah kecil elit menguasai mayoritas kekayaan dan lahan, sementara sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kemiskinan Pola ini mirip situasi feodal: tuan tanah kaya menguasai lahan, petani kecil menyewa atau menggarap dengan ketergantungan tinggi pada pemilik lahan Kesenjangan antara golongan atas dan bawah melebar, dan mobilitas sosial pun terhambat Hal ini diperburuk oleh akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan pekerjaan; banyak rakyat jelata tidak mampu mengakses pendidikan dan peluang kerja setara kaum elit, sehingga sulit naik kelas sosial Warisan feodalisme inilah yang hingga kini menjadi tantangan bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih adil dan maju.
Kemiskinan, Pendidikan, dan Penguatan Struktur Feodal
Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor-faktor yang membuat struktur feodal terus lestari di Indonesia. Pada tingkat sosial, budaya patron-klien masih sangat kuat karena kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, ditambah tingkat pendidikan yang rendah Kelompok masyarakat miskin cenderung bergantung pada patron (pelindung), misalnya tokoh berpengaruh atau pemuka agama setempat, untuk mendapatkan bantuan finansial, pekerjaan, atau keamanan. Ketergantungan ekonomi ini membuat mereka enggan atau sulit bersikap kritis terhadap sang patron. Sebagai balasan atas bantuan, mereka memberikan kepatuhan dan penghormatan penuh, mempertahankan pola hubungan hierarkis tradisional. Dengan demikian, kemiskinan menciptakan kondisi yang membutuhkan patronase, yang pada gilirannya memperkuat relasi ala feodalisme di tingkat lokal.
Di sisi lain, pendidikan yang rendah membuat sebagian masyarakat tidak kritis terhadap struktur sosial yang timpang. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak warga, kesetaraan, dan prinsip-prinsip demokratis menyebabkan penerimaan pasif terhadap status quo hierarkis. Masyarakat yang tidak terpapar pendidikan luas cenderung menerima kepemimpinan berbasis status keturunan atau tradisi tanpa mempertanyakan kompetensi atau legitimasi pemimpin tersebut. Ini selaras dengan temuan bahwa budaya patron-klien dan feodalisme “terpelihara” oleh faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan Ketergantungan ekonomi membuat orang enggan menentang patron, sementara keterbatasan edukasi membuat mereka tidak menyadari alternatif hubungan sosial yang lebih egaliter.
Sebagai contoh, di banyak daerah pedesaan, seorang kepala adat atau kiai lokal yang berpengaruh sering menjadi tumpuan warga miskin untuk berbagai urusan – dari bantuan bahan pokok hingga mediasi konflik. Posisi tawar warga di hadapan tokoh tersebut sangat lemah, sehingga muncul ketaatan berlebihan layaknya bawahan kepada majikan. Begitu pula dalam politik elektoral, politisi kerap memanfaatkan kemiskinan dan pendidikan rendah dengan politik uang atau bantuan sesaat; rakyat miskin disuguhi bantuan sembako atau uang menjelang pemilu demi suaranya, sebuah praktik patronase klasik Setelah terpilih, sang pejabat cenderung abai terhadap janji, mempertahankan kekuasaan bagi kelompoknya sendiri Pola ini melanggengkan siklus klientelisme rakyat kecil terus bergantung dan elit terus dominan.
Lebih lanjut, akses pendidikan yang timpang memperparah feodalisme modern. Pendidikan sejatinya membuka jalan mobilitas sosial, namun ketika aksesnya terbatas pada golongan berada saja, struktur kelas menjadi kaku. Orang-orang yang memiliki privilege (misal dari keluarga terpandang) dapat mengenyam pendidikan tinggi dan mempertahankan dominasinya, sementara kalangan tidak mampu tertinggal. Ketidakmampuan masyarakat bawah mengakses pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan elit memperburuk ketimpangan, sehingga jarak sosial semakin lebar Dalam situasi demikian, loyalitas tradisional kepada figur elit dianggap “wajar” karena dianggap sudah takdir sosial. Hal ini semuanya menunjukkan bahwa kemiskinan dan kurangnya pendidikan berkontribusi besar menjaga pola-pola feodal tetap hidup.
Kultus Gelar Habib, Gus, dan Kyai dalam Masyarakat
Fenomena khusus feodalisme di Indonesia tampak dalam kultus gelar-gelar religius seperti Habib, Gus, dan Kyai. Gelar-gelar ini pada dasarnya berasal dari tradisi Islam Nusantara, namun dalam perkembangan sosial tertentu memperoleh posisi istimewa bak gelar kebangsawanan. Habib adalah sebutan bagi mereka yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad (khususnya dari komunitas Arab Hadramaut/Sayahid di Indonesia). Kyai (atau Kiai) adalah gelar kehormatan bagi ulama atau tokoh agama senior, terutama pimpinan pesantren di Jawa. Adapun Gus (bahasa Jawa halus, asalnya dari kata “bagus”) digunakan untuk menyapa putra seorang kyai, semacam panggilan hormat bagi “anak cucu” tokoh agama.
Pada awalnya, penggunaan gelar-gelar tersebut bersifat sederhana dan fungsional – sekadar penanda status keluarga atau posisi sosial di komunitas. “Gus” misalnya awalnya hanya panggilan akrab untuk putra kyai di Jawa, dan “Habib” hanyalah sebutan untuk orang Arab yang nasabnya tersambung ke Nabi
Dalam konteks tradisional, panggilan ini tidak otomatis berarti pemuliaan berlebihan, melainkan penghormatan wajar kepada keturunan orang alim atau keturunan Rasulullah. Namun, seiring waktu terjadi inflasi makna karena penghormatan berlebihan dari masyarakat Gelar-gelar ini bukan lagi sekadar identitas keluarga, tapi berubah menjadi simbol sakral yang kebal kritik
Di Jawa, seorang “Gus” diasosiasikan dengan trah (garis keturunan) kyai terkemuka. Publik menaruh ekspektasi bahwa si Gus kelak akan meneruskan kepemimpinan pesantren atau peran ulama ayahnya. Gelar ini membawa semacam “hak istimewa” implisit sejak lahir – masyarakat lokal bahkan menyebut para Gus dan Ning (putri kyai) sebagai “pangeran/pangeran cilik”, menandai status mereka sebagai pewaris yang dimuliakan Keistimewaan ini berakar dari kepercayaan sosial dan pemahaman keagamaan paralel tentang bagaimana wali (orang suci), ahli waris, dan keluarga mereka seharusnya diperlakukan Artinya, ada justifikasi budaya-religius bahwa “darah biru” ulama pantas dihormati layaknya darah biru bangsawan.
Demikian pula, gelar “Habib” membawa konotasi spiritual tinggi. Seorang habib dianggap memiliki kemuliaan tersendiri sebagai dzurriyat (keturunan) Rasulullah, sehingga umat merasa wajib memuliakannya Dalam Islam memang diajarkan agar mencintai Ahlul Bait (keluarga Nabi) – Rasulullah sendiri berpesan kepada umat agar menghormati keluarga dan keturunannya Realitas ini membuat gelar Habib di Indonesia otomatis ditempatkan di strata sosial atas seorang habib sering dipandang lebih “suci” atau berwibawa dalam urusan agama dibanding ustaz/kyai biasa. Namun, banyak kasus menunjukkan penghormatan yang berlebihan justru mengaburkan makna asli gelar tersebut Gelar Habib yang seharusnya menandai nasab mulia kini berubah menjadi simbol otoritas yang kadang tidak sejalan dengan kapasitas pribadi atau akhlak pemilik gelar Dengan kata lain, masyarakat telanjur menyanjung gelar ketimbang menilai kompetensi dan integritas individu yang menyandangnya.
Hal serupa terjadi pada gelar Kyai. Seorang kyai dalam tradisi pesantren memiliki wibawa amat besar, dipandang sebagai figur karismatik yang ilmunya “tanpa tanding” di komunitasnya Tradisi pesantren menciptakan hierarki tegas kyai di puncak, kemudian para santri senior, hingga santri junior. Hubungan kyai-santri sangat vertical dan paternalistik, sehingga sebagian menilai ini sebagai bentuk feodalisme modern Pengkultusan terhadap figur kyai begitu kuat dalam kultur pesantren Jawa, hingga kyai cenderung ditempatkan pada posisi superior dan “tidak boleh salah” di mata pengikutnya Superioritas kyai ini menjadi semacam identitas feodal yang melekat di pesantren, karena kepatuhan santri sangat tinggi dan nyaris tanpa interupsi terhadap perintah kyainya.
Mengapa gelar-gelar ini begitu dikultuskan? Selain faktor nasab dan tradisi lokal, ada dimensi teologis dan kultural Islam Nusantara yang berperan. Masyarakat meyakini keberkahan (barokah) bisa mengalir melalui keturunan orang saleh. Keluarga ulama dianggap mewarisi karomah (kemuliaan spiritual) pendahulunya. Dalam teks-teks klasik, ada konsep “al-ʿilm yuraa wa laa yaroets” (ilmu itu dilihat, tidak diwariskan), tapi pada praktiknya masyarakat awam sering menganggap ilmu dan karisma kyai menurun kepada anaknya. Akibatnya, muncul penghormatan turun-temurun: anak-cucu kyai (Gus/Ning) langsung dihormati sejak belia, meskipun mereka pribadi belum menunjukkan prestasi apa pun.
Lebih kritis lagi, kultus gelar ini terkadang melampaui batas wajar. Pemujaan berlebihan menjadikan figur bergelar seperti “manusia setengah dewa”. Banyak yang menganggap seorang Habib pasti lebih benar ucapannya, seorang Gus pasti pantas jadi pemimpin, hanya karena gelarnya – bukan karena usaha atau keilmuannya. Hierarki sosial menjadi kaku, di mana mereka yang menyandang gelar tertentu memperoleh privilege tanpa perlu membuktikan kompetensi Masyarakat cenderung menilai orang dari gelarnya ketimbang prestasi dan kontribusi nyata. Ini jelas bertentangan dengan prinsip egalitarianisme, baik secara demokratis maupun menurut ajaran Islam yang menilai kemuliaan manusia dari takwanya, bukan dari keturunannya.
Patut dicatat, kecenderungan mengkultuskan gelar ini tidak diterima di semua kalangan Muslim Indonesia. Misalnya, ormas Muhammadiyah sejak awal terkenal lebih egaliter dan anti kultus individu. Dalam budaya Muhammadiyah, pemimpin agama cukup dipanggil “ustaz” atau “KH” (kiai haji) tanpa embel-embel nasab Bahkan anak atau cucu pendiri Muhammadiyah (KH. Ahmad Dahlan) pun tidak diberi keistimewaan gelar apapun, meski nasabnya tersambung ke Nabi Muhammad SAW Seorang penulis mencatat bahwa tradisi di lingkungan Muhammadiyah tidak mengenal “Habib” karena mereka tidak terbiasa menyematkan kultus nasab seseorang; nilai yang dijunjung adalah musyawarah dan kepemimpinan kolektif, bukan garis keturunan Perbedaan kultur ini menunjukkan bahwa sebenarnya ajaran Islam bisa ditafsirkan secara egaliter, namun pada komunitas lain (terutama kalangan tradisionalis) aspek penghormatan kepada nasab mulia lebih dominan.
Perspektif Budaya dan Islam terhadap Fenomena Ini
Dari perspektif budaya, pengkultusan gelar Habib, Gus, dan Kyai bisa dipahami sebagai lanjutan dari tradisi hierarkis yang telah lama mengakar. Banyak suku di Indonesia (terutama Jawa) memang memiliki adat menghormati figur pemimpin atau tetua secara sangat tinggi. Budaya paternalistik Jawa misalnya, mengajarkan unggah-ungguh (tata krama) yang ketat dalam menghormati orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya, entah karena usia, ilmu, maupun garis darah. Ketika Islam berkembang di Nusantara, nilai-nilai lokal tersebut berasimilasi dengan penghormatan kepada ulama dan habaib. Hasilnya, sinkretisme budaya dan agama masyarakat memandang ulama besar hampir seperti bangsawan, lengkap dengan “kerajaan”-nya berupa pesantren atau majelis taklim, serta “pewaris tahta”-nya berupa putra-putri mereka.
Secara sosiologis, hal ini menjadikan pesantren atau komunitas keagamaan tradisional layaknya miniatur masyarakat feodal. Ada stratifikasi sosial jelas: kyai (elite spiritual), para santri senior/staf (kelas menengah), dan santri junior/jamaah awam (kelas bawah). Namun, beberapa ahli dan tokoh pesantren berargumen bahwa hierarki di pesantren bersifat fungsional, bukan penindasan sewenang-wenangOtoritas kyai didasarkan pada keilmuan dan moralitas yang diakui, bukan semata-mata kekuasaan turun-temurun Tradisi keilmuan Islam memang menempatkan guru sangat dihormati, tetapi juga mensyaratkan sang guru berakhlak mulia dan alim dalam agama Dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim, murid dianjurkan berhati-hati memilih guru, memastikan gurunya benar-benar orang ‘alim dan wara’ (menjauhi hal tercela) Ini berarti kepatuhan murid ada batasnya: tidak semua perintah guru wajib diikuti bila bertentangan dengan syariat dan akal sehat Contoh yang diangkat KH. Baha’uddin Nursalim (Gus Baha’) – seorang ulama muda NU – adalah kisah Nabi Musa yang mempertanyakan tindakan Nabi Khidir ketika melihat hal yang tampak melanggar norma (membunuh anak kecil). Musa AS melakukan itu sebagai penegasan komitmennya terhadap syariat, meskipun Khidir adalah gurunya Pesan dari kisah ini: murid boleh kritis jika sang guru (atau pemimpin) tampak menyimpang dari ajaran yang benar.
Dari perspektif ajaran Islam sendiri, sebenarnya terdapat penekanan kuat pada egalitarianisme dan keadilan. Al-Qur’an menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan keturunan atau status sosial (QS 49:13). Nabi Muhammad juga mengajarkan kesederajatan: pada Haji Wada’ (khutbah perpisahan), beliau bersabda “Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, atau orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali dengan takwa”. Prinsip ini semestinya mencegah pengagungan berlebih berdasarkan nasab. Bahkan, Nabi pernah menegur sahabat yang terlalu memujinya: “Jangan berlebihan memujiku seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam; aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya.” Itu menunjukkan Islam melarang kultus individu secara berlebihan, termasuk kepada Nabi sekalipun, apalagi kepada ulama atau keturunannya.
Namun, Islam juga mengajarkan adab menghormati ulama dan Ahlul Bait. Terdapat banyak hadits dan atsar yang menganjurkan memuliakan ‘alim ulama (karena mereka pewaris para nabi) serta mencintai keluarga Nabi. Seorang ulama besar Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menjelaskan bahwa umat Islam wajib menghormati dan mencintai Ahlul Bait Rasulullah, karena mereka memiliki kemuliaan khusus Ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur’an (QS Asy-Syura: 23) dan wasiat Nabi agar umat menjaga sikap terhadap kerabat beliau Akan tetapi, Al-Haddad mengingatkan jika ada di antara Ahlul Bait yang menyimpang dari jalan yang benar, umat wajib menasihati mereka Artinya, penghormatan tidak boleh berubah menjadi pembenaran buta. Kasih sayang kepada dzurriyat Nabi harus tetap disertai amar ma’ruf nahi munkar ketika diperlukan. Sikap inilah yang ideal: menghormati tanpa mengkultuskan.
Banyak ulama Nusantara sejalan dengan pandangan tersebut. Misalnya, Rais ‘Aam PBNU saat ini, KH. Miftachul Akhyar, pernah mengingatkan bahwa mencintai Habaib itu baik, tapi para Habib pun harus menjaga akhlak dan tidak menyalahgunakan kemuliaan nasab untuk hal tercela. Di lingkungan pesantren, kiai-kiai sepuh sering menasihati santri agar tawadu’ (rendah hati) tetapi tidak taklid buta. Ada ungkapan terkenal: “Guru itu bukan Tuhan, bisa salah; ilmu itu cahaya kebenaran, jangan dibutakan oleh figur.” Ini mengindikasikan bahwa dalam perspektif Islam, otoritas tetap diukur dari kebenaran ajarannya, bukan dari gelarnya semata.
Di sisi lain, beberapa ulama/cerdik cendekia juga mengkritik fenomena feodalisme berbalut agama ini. Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), tokoh budayawan Muslim, secara terang menyebut “feodalisme dengan kedok agama” sebagai sesuatu yang memprihatinkan Beliau menolak konsep bahwa karena seseorang bergelar habib atau gus lantas harus diperlakukan bak bangsawan. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), semasa hidupnya, juga menekankan prinsip egaliter dalam Islam. Gus Dur berasal dari keluarga kyai terpandang namun terkenal membumi dan demokratis ia kerap mengingatkan bahwa kepemimpinan Islam itu melayani umat, bukan minta dilayani. Pandangan-pandangan semacam ini menegaskan bahwa nilai budaya feodal sesungguhnya bertentangan dengan semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi sekalian alam) dan musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama.
Dampak Sosial dan Struktur Kekuasaan dari Kultus Gelar
Pengultusan berlebihan terhadap gelar Habib, Gus, dan Kyai membawa berbagai dampak sosial dan memengaruhi struktur kekuasaan di Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah terciptanya hierarki sosial yang kaku. Ketika masyarakat menilai seseorang lebih karena gelarnya ketimbang kapasitasnya, maka prinsip meritokrasi tergeser. Orang-orang yang menyandang gelar terhormat cenderung mendapat posisi atau privilese istimewa “di atas nampan”, tanpa proses seleksi yang ketat. Ini bisa dilihat misalnya dalam organisasi keagamaan atau politik lokal: putra seorang kyai kharismatik lebih mudah diterima menjadi pemimpin hanya karena status “Gus”-nya, meski mungkin ada orang lain yang lebih kompeten. Struktur kekuasaan jadi bias – loyalitas personal dan kekerabatan mengalahkan penilaian obyektif.
Dalam ranah politik, aura gelar religius sering dimanfaatkan sebagai modal elektoral. Seorang kandidat dengan gelar “Habib” atau “Gus” di depan namanya memiliki daya tarik emosional bagi konstituen Muslim tradisional Gelar tersebut menjadi label branding yang dapat menyedot simpati dan dukungan massa tanpa perlu menjelaskan rekam jejaknya. Tak jarang politikus mengundang habib atau kyai besar dalam kampanye untuk mendulang legitimasi religius. Fenomena ini bisa dilihat, misalnya, pada Pilpres 2019 ketika beberapa habaib terlibat terang-terangan mendukung calon tertentu, sehingga seolah muncul blok politik habaib/ulama. Di level daerah, bupati atau gubernur bergelar kyai/habib juga kerap memenangkan suara karena dianggap “wakil ulama”. Akibatnya, batas antara otoritas spiritual dan kekuasaan politik menjadi kabur, dan hal ini rentan disalahgunakan.
Dampak lain adalah longsornya otoritas agama yang sejati. Ketika hanya segelintir orang bergelar tertentu dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak, otoritas ulama kolektif justru melemah Publik cenderung mengikuti figur bergelar populer, sementara ulama lain yang mungkin lebih berilmu tapi tanpa gelar “elite” diabaikan. Bahkan, ada gejala “ustaz selebritas” yang muncul tanpa marga Habib/Gus tapi diberi gelar kehormatan agar dianggap sederajat. Tempo pernah mengungkap kasus jual-beli gelar Habib (April 2024) – di mana gelar habib diperjualbelikan di “pasar gelap” demi prestise Ini jelas merusak kesakralan gelar tersebut dan menunjukkan betapa title itu dipandang sebagai komoditas kekuasaan, bukan lagi murni nasab. Orang yang tidak punya hubungan keluarga Nabi pun bisa membeli gelar habib demi dihormati laiknya “darah biru”.
Sementara itu di komunitas pesantren, pengaruh feodal bisa berdampak pada regenerasi kepemimpinan dan kreativitas santri. Karena kultur paternalistik yang kuat, sering kali jabatan pengasuh pesantren diwariskan ke putra kyai (Gus) meski mungkin ada santri senior lain yang mumpuni. Ini bisa menyebabkan monopoli kekuasaan dalam lingkup pesantren oleh trah keluarga tertentu. Bagi santri, kreativitas dan mobilitas sosial bisa terhambat ketika mereka “harus tunduk” secara vertikal. Ada kekhawatiran dari pengamat bahwa hal ini dapat menutup kritik internal dan inovasi di lembaga pendidikan tradisional, jika semua keputusan terpusat pada satu figur kharismatik. Meski di satu sisi menjamin kontinuitas tradisi, di sisi lain dapat mengurangi dinamika pembaruan.
Lebih jauh, pengkultusan gelar tanpa filter menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus penipuan berkedok agama marak terjadi, memanfaatkan kepercayaan buta masyarakat terhadap gelar. Contohnya, insiden Eko Supriyanto yang mengaku sebagai “Gus” fiktif (Gus Juan) di Kalimantan Selatan demi menipu orang tahun 2021. Dengan modal gelar tersebut, ia berhasil meyakinkan korban bahwa dirinya figur spiritual terhormat, hingga banyak yang tertipu secara materiil maupun immateriilKasus lain, beberapa tahun lalu terdapat “Habib palsu” yang ketahuan bukan keturunan Nabi namun telah terlanjur dihormati dan mengumpulkan sumbangan besar dari masyarakat. Praktik penipuan semacam ini sangat merugikan umat dan mencoreng institusi keagamaan. Masyarakat menjadi skeptis terhadap figur agama, bahkan yang asli, karena sulit membedakan mana yang tulus berilmu dan mana yang hanya berbekal gelar Kepercayaan publik terhadap tokoh agama bisa rontok apabila berulang kali dikecewakan oleh perilaku oknum bergelar tersebut.
Dampak negatif lainnya terlihat ketika gelar lebih dihargai daripada kompetensi dalam birokrasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah/otoritas mengangkat seseorang ke jabatan publik terutama karena popularitas gelar religiusnya, bukan semata kapasitas. Misal yang disoroti media: penunjukan seorang pendakwah terkenal “Gus Miftah” (Miftah Maulana Habiburrahman) sebagai pejabat Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama oleh Presiden (sebut saja dalam contoh ini Presiden fiktif) mendapat kritik. Publik mempertanyakan, apakah pemilihan tersebut didasari keahlian dan integritas, atau sekadar balas jasa atas dukungan politik?. Keputusan semacam ini jika benar terjadi, hanya akan memperkuat budaya feodal dan mengaburkan standar kompetensi dalam penunjukan pejabat . Dalam jangka panjang, meritokrasi hancur dan muncul preseden buruk bahwa gelar sosial lebih penting dari kapabilitas. Hal ini bisa menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik maupun keagamaan, karena rakyat melihat orang yang diangkat bukan lagi yang terbaik, melainkan yang “berdarah biru” atau punya kedekatan khusus.
Secara moral-sosial, kultus berlebihan juga membawa efek korosif. Masyarakat bisa terjebak dalam taqlid buta, menerima apa pun kata sang tokoh bergelar tanpa proses kritis. Padahal, jika ternyata tokoh tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran moral, dampaknya bisa menimbulkan kekecewaan kolektif yang meruntuhkan sendi moral umat. Contohnya, ketika muncul skandal atau perilaku tidak etis dari oknum habib/kyai (misal kasus kekerasan atau asusila), banyak pengikut yang syok dan kehilangan panutan. Sebagian mungkin justru menyangkal fakta atau membelanya habis-habisan (karena terlanjur kultus), namun sebagian lain jadi apatis terhadap agama. Ini berbahaya karena erosi nilai-nilai keagamaan bisa terjadi – orang menjadi sinis terhadap figur agama secara umum akibat ulah segelintir yang dikultuskan lalu jatuh Ujungnya, institusi agama kehilangan wibawa, dan ruang tumbuhnya nilai spiritual dalam masyarakat menyempit.
Penutup: Menuju Masyarakat yang Kritis dan Egaliter
Fenomena feodalisme dalam balutan budaya dan agama seperti di Indonesia ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, penghormatan kepada ulama dan keturunan Nabi mencerminkan tradisi beradab dan kecintaan kepada hal-hal yang dianggap mulia. Namun di sisi lain, ketika penghormatan berubah menjadi pemujaan buta, ia menjelma belenggu yang menghambat kemajuan sosial. Solusi yang diusulkan banyak cendekiawan dan ulama progresif adalah mendorong masyarakat bersikap lebih kritis dan proporsional. Penghormatan tetap perlu – menghormati guru, ulama, habaib adalah akhlak terpuji – tetapi harus didasarkan pada nilai integritas, ilmu, dan kontribusi nyata seseorang, bukan semata latar belakang keturunannya.
Untuk itu, perlu ditumbuhkan kesadaran tentang pentingnya meritokrasi dan egalitarianisme dalam Islam dan kehidupan berbangsa. Pendidikan menjadi kunci: melalui pendidikan formal maupun nonformal, masyarakat perlu diajak memahami bahwa gelar hanyalah simbol, sedangkan kapasitas dan akhlak adalah esensi yang hakiki Seorang habib atau gus yang benar-benar berilmu dan berakhlak tentu patut dihormati – bukan karena gelarnya, melainkan karena ilmunya yang bermanfaat. Sebaliknya jika tidak berkompeten atau menyimpang, harus berani dikritik meski ia bergelar tinggi. Sikap tabayyun (clarification) dan nasehat-menasehati dalam kebenaran harus ditegakkan melebihi rasa segan hierarkis.
Dari sisi struktural, diperlukan transparansi dan aturan untuk mencegah penyalahgunaan gelar. Misalnya, komunitas habaib bisa memperketat validasi nasab agar tidak ada “habib gadungan” yang menipu umat. Lembaga pemerintah pun idealnya tidak menunjuk seseorang semata karena popularitas gelarnya tanpa verifikasi kredibilitas. Dalam lingkungan pesantren, beberapa kyai sudah mulai melibatkan unsur musyawarah santri atau dewan pengajar dalam mengambil keputusan, alih-alih one-man rule. Langkah-langkah kecil ini diharapkan mengurangi sifat sentralistik-feodalistik yang dikhawatirkan.
Inti dari semuanya, penyadaran kolektif perlu dibangun bahwa tidak ada manusia yang kebal kritik. Mengkritisi kultus gelar bukan berarti anti-ulama atau anti-Ahlul Bait, justru demi menjaga kemurnian ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kebenaran. Seperti kata pepatah, “Hormatilah orangnya, tapi lebih hormati lagi kebenaran yang dibawanya.” Dengan masyarakat yang lebih berpendidikan dan sejahtera, pola patronase feodal akan melemah Pada akhirnya, kita berharap terbentuk masyarakat madani yang egaliter dan bermartabat, di mana takzim kepada tokoh diberikan sepantasnya, tanpa harus terjerat feodalisme yang membelenggu nalar dan keadilan
ASAHANSATU.CO.ID
. Referensi:
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 2011).
Husen, Anita F., “Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients,” Jurnal Pendidikan IPS Vol. 14 No. 2 (2024): 262-270
RESEARCHGATE.NET
.
Ilahi, Mohammad Takdir. “Kiai: Figur Elite Pesantren,” Jurnal Kebudayaan Islam Vol. ? (PDF)
DOWNLOAD.GARUDA.KEMDIKBUD.GO.ID
DOWNLOAD.GARUDA.KEMDIKBUD.GO.ID
.
Artikel “Feodalisme dalam Pemujaan Gelar Gus dan Habib: Antara Tradisi dan Penyalahgunaan,” Asahansatu (2 Maret 2025)
.
Artikel “Di Balik Tuduhan Feodalisme dalam Tubuh Pesantren,” Tebuireng Online
TEBUIRENG.ONLINE
.
Majid Himawan, “Kenapa Tidak Ada Orang dengan Gelar Habib di Muhammadiyah?” Mojok.co (23 Nov 2020)
MOJOK.CO
NU Online, “Keharusan Menghormati Ahlul Bait dan Menasihati jika Mereka Menyimpang” (3 Des 2018)
NU.OR.ID
.
Kompasiana, “Feodalisme: Penghalang Kemajuan Indonesia”
KOMPASIANA.COM
.
What's Your Reaction?